Sarjana Menganggur Dan Revolusi Pendidikan Tinggi
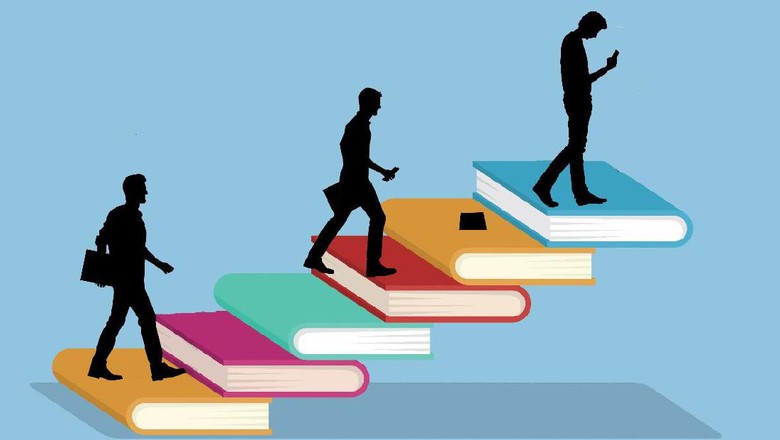 Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcomJakarta -
Lembaga pemeringkat perguruan tinggi tinggi Quacquarelli Symonds (QS) pada pekan kemudian merilis laporan QS Graduate Employability Rankings 2020. Laporan tersebut menyusun peringkat 500 universitas di dunia berdasarkan persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan.
Menariknya, berdasarkan Direktur Riset QS Ben Sowter, tidak ada hubungan yang terperinci antara prestise sebuah universitas dengan kemampuan lulusannya mendapat pekerjaan. Contohnya di Indonesia, Universitas Bina Nusantara yang menempati posisi papan bawah (801-1000) dalam QS World University Rankings justru mendapat skor dan peringkat employability yang sejajar dengan Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung yang menduduki posisi papan atas dalam QS World University Rankings.
Terlepas dari pro-kontra metode analisis yang dipakai oleh QS, analisis Ben Sowter tersebut kiranya sanggup menjadi peringatan bagi semua perguruan tinggi tinggi di Tanah Air untuk tidak melupakan nasib lulusannya di tengah semangat kompetisi antar perguruan tinggi tinggi untuk menaikkan prestise di tingkat nasional maupun internasional.
Masih Stabil
Tingginya tingkat pendidikan ternyata tidak menjamin mudahnya mendapat pekerjaan. Data Biro Pusat Statistik 2019 memperlihatkan tingkat pengangguran lulusan diploma dan universitas masing-masing berada di kisaran 6 hingga 7 persen, jauh di atas tingkat pengangguran lulusan SD (2,7 persen) dan Sekolah Menengah Pertama (5 persen).
Karakteristik lapangan pekerjaan di Indonesia masih didominasi oleh sektor yang tidak memerlukan kualifikasi pendidikan tinggi, yaitu sektor pertanian dan perdagangan yang menyerap hampir 50 persen dari 130 juta tenaga kerja. Dan menariknya, salah satu pengaruh counter-intuitive dari Revolusi Industri 4.0 yaitu munculnya jenis-jenis pekerjaan gres yang tidak menuntut seseorang untuk mempunyai ijazah perguruan tinggi tinggi tetapi memperlihatkan honor yang lumayan. Layanan transportasi berbasis online misalnya, sanggup mengatakan pendapatan yang tidak mengecewakan dengan waktu kerja yang fleksibel.
Mayoritas masyarakat Indonesia menganut konsumerisme di mana pendidikan masih dianggap sebagai komoditas yang dilihat dari aspek untung-rugi. Biaya kuliah yang semakin mahal tanpa adanya jaminan mendapat pekerjaan yang layak mengakibatkan pilihan masuk ke perguruan tinggi tinggi sebagai investasi merugi. Jika hal ini tidak diatasi, isu terkini masyarakat untuk kuliah dikhawatirkan akan menurun. Akibatnya nasib 4600 institusi pendidikan tinggi kita akan berada di ujung tanduk.
Di Amerika Serikat misalnya, jumlah mahasiswa gres terus mengalami penurunan selama 9 tahun berturut-turut semenjak 2011 hingga sekarang. Salah satu faktor yang menjadi alasannya yaitu penurunan minat kuliah yaitu membaiknya perekonomian Amerika selama 10 tahun terakhir yang mengakibatkan mudahnya mendapat pekerjaan yang membutuhkan keterampilan rendah. Konsekuensinya, jumlah perguruan tinggi tinggi yang bangkrut terus meningkat.
Sejak 2016, 23 perguruan tinggi tinggi swasta dan 32 perguruan tinggi tinggi negeri harus ditutup atau dipaksa melaksanakan merger. Diperparah lagi dengan angka putus kuliah (drop-out) yang dikala ini berada di angka kritis 40%. David Kirp membahas krisis drop-out ini dalam buku terbarunya The College Drop-out Scandal (2019).
Di Indonesia sendiri, data Kemenristekdikti memperlihatkan jumlah mahasiswa gres masih stabil di angka 1,4 juta mahasiswa per tahun semenjak 2014 hingga 2018. Angka ini diperlukan akan terus meningkat seiring dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat. Demikian pula dengan angka putus kuliah yang masih berada di kisaran 1-4 persen. Tetapi dunia pendidikan tinggi di Indonesia dihentikan berdiam diri. Krisis yang terjadi di Amerika Serikat bisa saja terjadi di Indonesia jikalau pendidikan tinggi kita tidak direvitalisasi.
Harus Berbenah
Untuk menjaga kepercayaan publik, dunia pendidikan tinggi kita harus berbenah. Diperlukan sebuah model gres pendidikan tinggi yang sanggup mengikuti cepatnya perkembangan zaman. Ironisnya, dominan universitas di seluruh dunia dikala ini masih menganut model yang dicetuskan oleh filsuf Jerman Wilhelm von Humboldt pada awal kala ke-19. Mustahil dunia pendidikan tinggi bisa mengikuti perkembangan jaman jikalau modus operandinya tidak berubah selama 200 tahun!
David Staley dalam bukunya Alternative Universities: Speculative Design for Innovation in Higher Education (2019) mengajukan beberapa model gres yang bisa diadopsi oleh dunia pendidikan tinggi. Salah satu model yang cukup menarik yaitu Polymath University --setiap mahasiswa mengambil tiga disiplin ilmu (triple majors), contohnya akuntasi-fisika-sejarah, bisnis-sosiologi-filsafat, keuangan-astronomi-agama, atau beberapa kombinasi lain. Lahirnya wangsit Polymath University didasari oleh realitas dunia pekerjaan dikala ini yang membutuhkan lulusan universitas yang bisa berpikir kreatif, lintas ilmu, dan multidimensi.
Kemudian ada pula model Interface University, di mana mahasiswa dan dosen berinteraksi pribadi dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Model universitas ini dilatarbelakangi oleh semakin terintegrasinya kecerdasan buatan dalam sektor industri dan jasa. Lulusan universitas harus bisa berinteraksi dan berpikir bersama komputer, bukan hanya sekedar menggunakannya.
Revolusi dunia pendidikan tinggi yaitu proses yang tidak mudah. Hanya ada tiga institusi yang nyaris tidak berubah selama 200 tahun: institusi agama, monarki, dan universitas. Revolusi harus dimulai dari kini sebelum masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pendidikan tinggi. Saya mengusulkan tiga taktik utama untuk menginisiasi revolusi dunia pendidikan tinggi.
Pertama, perombakan kurikulum (curriculum revamp) dengan melibatkan dunia industri dalam penyusunan dan implementasi kurikulum baru. Untuk menyesuaikan isi kurikulum dengan perkembangan zaman, perombakan dilakukan secara bersiklus setiap 3-5 tahun dan dievaluasi setiap tahun. Dunia industri terlibat secara aktif dalam proses revamp sebagai penasihat. Mereka mengevaluasi dan mengusulkan kandungan kurikulum yang sesuai dengan praktik-praktik terbaru di dunia industri dan jasa. Mereka juga terlibat secara aktif sebagai tenaga pengajar pertolongan (adjunct) dalam mata kuliah tertentu.
Kedua, memperkuat keunikan (difference) dan keistimewaan (distinction) setiap kegiatan studi yang ada. Sebagai contoh, kepala kegiatan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas A harus menciptakan programnya berbeda dengan kegiatan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas B. Lulusan setiap prodi dari universitas berbeda akan mempunyai keunikan dan keistimewaan yang memberi nilai tambah kepada kualitas dan kompetensi lulusan. Universitas juga didorong untuk menciptakan program-program studi gres yang unik untuk mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ketiga, kegiatan magang (internship) yang diintegrasikan dalam kurikulum. Kabar gembiranya, tahun ini Kemenristekdikti tetapkan bahwa 45 jam kerja magang setara dengan satu satuan kredit semester (SKS) sehingga mahasiswa tidak kehilangan SKS selama proses magang. Ke depannya, magang sanggup dinaikkan statusnya sebagai kegiatan wajib dengan beban SKS tertentu.
Tentu saja revolusi dunia pendidikan tinggi harus didukung oleh seluruh pemegang kepentingan, mulai dari Kemenristekdikti, universitas, tenaga pengajar, dan mahasiswa. Tidak ada perubahan yang nyaman. Setiap perubahan niscaya mendobrak kenyamanan. Tetapi akan lebih tidak nyaman jikalau perguruan tinggi tinggi harus bangkrut lantaran kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
Bimo Ario Tejo associate professor dan dekan Faculty of Applied Sciences (2016-2019) UCSI University, Malaysia
Sumber detik.com


Belum ada Komentar untuk "Sarjana Menganggur Dan Revolusi Pendidikan Tinggi"
Posting Komentar